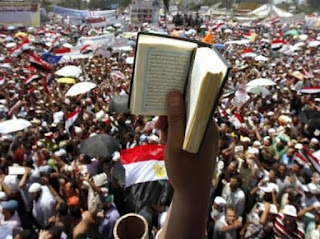RESENSI BUKU
Judul
|
:
|
Hukum tentang Ekstradisi
|
Penulis buku
|
:
|
Prof. Dr. Romli Atmasasmita, SH., LL.M
|
Penerbit
|
:
|
Fikahati Aneska
|
Bahasa
|
:
|
Indonesia
|
Jumlah halaman
|
:
|
x + 389
|
Tahun penerbitan
|
:
|
2011
|
Pembuat resensi
|
:
|
AM. Sidqi
|
 |
| Resensi ini dimuat di Jurnal Opinio Juris vol. 13 tahun 2013, terbitan Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional, Kementerian Luar Negeri RI |
Perdebatan-perdebatan seputar hukum tentang ekstradisi tersebut memunculkan pertanyaan mendasar yang wajib dipahami oleh semua: apa dan bagaimana perkembangan hukum tentang ekstradisi tersebut?
Buku berjudul
“Hukum tentang Ekstradisi” yang ditulis oleh Prof. Dr. Romli Atmasasmita, SH.,
LL.M ini hadir untuk mencerahkan publik perihal definisi, karakteristik, dan
perkembangan pelbagai model tentang ekstradisi. Kepakaran Prof. Dr. Romli
Atmasasmita, SH., LL.M sebagai salah satu ahli dalam hukum mengenai ekstradisi
tidak lagi diragukan, mengingat Romli memiliki daftar panjang pengalaman sebagai
ketua delegasi pemerintah Indonesia ke berbagai konferensi PBB yang membahas
kejahatan transnasional.
 |
| Cover buku Hukum tentang Ekstradisi" karya Romli Atmasasmita |
Berdasarkan UU
1/1979 tentang Ekstradisi, Ekstadisi diartikan sebagai penyerahan oleh suatu
negara kepada negara yang meminta penyerahan seseorang yang disangka tau
dipidana karena melakukan suatu kejahatan di luar wilayah negara yang
menyerahkan dan di dalam yurisdiksi wilayah negara yang meminta penyerahan
tersebut karena berwenang untuk mengadili dan memindananya.
Praktik
perjanjian ekstradisi bagi Indonesia bukan masalah hukum baru karena setelah
kemerdekaan RI, Indonesia telah mengikatkan diri ke dalam perjanjian ekstradisi
dengan lima negara, yakni Malaysia, Filipina, Thailand, Australia; dua
perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana (mutual legal assistance treaty), yakni
dengan Australia dan RRT; dan satu perjanjian penyerahan pelanggar hukum yang
melarikan diri antara Indonesia dengan Hongkong.
Pemerintah
Indonesia juga telah menandatangani satu perjanjian regional dalam bantuan hukum
timbal balik dalam masalah pidana, yaitu UU 15/2008 antara Pemerintah Republik
Indonesia dengan Pemerintah Brunei Darussalam, Kamboja, Laos, Filipina,
Singapura, dan Vietnam yang telah ditandatangani tanggal 29 November 2009. Perjanjian-perjanjian
tersebut merupakan perkembangan penting pasca kemerdekaan dalam bidang
pencegahan dan pemberantasan kejahatan yang bersifat transnasional dan
terorganisasi yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia.
Lebih jauh lagi,
Indonesia telah memiliki UU 1/2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah
Pidana sebagai undang-undang payung (umbrella
act) untuk kerja sama dalam prosesl penyelidikan, penyidikan, dan
penuntutan tindak pidana serta perampasan asset tindak pidana. Begitu pula
Indonesia telah mempunyai UU 1/1979 tentang Ekstradisi sebagai payung hukum untuk
proses negosiasi membahas draf perjanjian ekstradisi dengan Negara lain.
Sekalipun demikian pemerintah Indonesia dalam praktik bersikap fleksibel
seperti di dalam perundingan draft teks perjanjian ekstradisi antara Repubik
Indonesia dengan Republik Korea, di mana Indonesia sepakat untuk tidak
menggunakan daftar kejahatan (list of
crime) yang dapat diekstradisikan. Penjelasan UU 42/2007 tentang Perjanjian
Ekstradisi antara Republik Indonesia dan Republik Korea menegaskan bahwa
dihapuskannya system daftar kejahatan (system elective)—sekalipun UU 1/1979
tersebut menganut sistem enumeratif—adalah untuk mengantisipasi perkembangan
kejahatan transnasional yang baru.
Buku yang terbit
pada tahun 2011 ini disusun dalam empat bab, yakni asal-usul dan karakteristik
ekstradisi (bab I); prinsip umum ekstradisi yang diakui dalam hukum internasional
dan beberapa pengecualian (bab II); perkembangan praktik ekstradisi dan
perbandingan model-model ekstradisi (bab III); dan pentutup yang berisi
pandangan dan sikap penulis terhadap perkembangan ekstradisi dan masalah yang
berkaitan dengan berbagai model hukum tentang ekstradisi (bab IV).
Pada bab I,
Romli Atmasasmita mengkritik pengertian ekstradisi yang sering diucapkan banyak
orang termasuk praktisi hukum, tetapi belum dipahami makna sesungguhnya dari
pengertian istilah tersebut. Sering disebutkan bahwa ditinjau dari asal
katanya, istilah ekstradisi (extradition, l’extradition) berasal dari bahasa
latin :”extradere”. Ex berarti keluar, sedangkan tradere berarti menyerahkan.
Kata bendanya adalah extraditio artinya penyerahan. Sedangkan menurut Romli,
pemaknaan pengertian istilah tersebut sangat menyesatkan karena tidak benar.
Romli mendefinisikan ekstradisi secara etimologis berasal dari dua suku kata, yaitu “extra” dan “tradition”. Sehingga demikian, ekstradisi berarti suatu konsep hukum yang berlawanan dengan “tradisi” yang telah berabad-abad dipraktikan antarbangsa-bangsa. Praktik tradisi tersebut adalah kewajiban setiap negara untuk menjadi pelindung (asylum) bagi siapa saja yang memohon perlindungan, dan tradisi untuk memelihara kehormatan (hospitality) sebagai negara tuan rumah atas mereka yang memohon perlindungan tersebut. Praktik asylum yang mendahului ekstradisi menunjukan bahwa ekstradisi merupakan kekecualian dari asylum.
 |
| M. Nazaruddin, mantan bendaraha Partai Demokrat |
Romli mendefinisikan ekstradisi secara etimologis berasal dari dua suku kata, yaitu “extra” dan “tradition”. Sehingga demikian, ekstradisi berarti suatu konsep hukum yang berlawanan dengan “tradisi” yang telah berabad-abad dipraktikan antarbangsa-bangsa. Praktik tradisi tersebut adalah kewajiban setiap negara untuk menjadi pelindung (asylum) bagi siapa saja yang memohon perlindungan, dan tradisi untuk memelihara kehormatan (hospitality) sebagai negara tuan rumah atas mereka yang memohon perlindungan tersebut. Praktik asylum yang mendahului ekstradisi menunjukan bahwa ekstradisi merupakan kekecualian dari asylum.
Hukum ekstradisi
merupakan cabang dari hukum pidana internasional yang mengatur prosedur
penyerahan tersangka, terdakwa, atau terpidana dari satu negara ke negara lain
untuk tujuan penuntutan atau menjalani hukuman. Hukum ekstradisi dilandaskan
pada asumsi bahwa negara yang meminta ekstradisi (requisting state) mempunyai
itikad baik dan pelaku kejahatan yang diserahkan akan diperlakukan adil selama
diadili di negara tersebut. Sesungguhnya, ekstradisi merupakan perwujudan dari
asas aut dedere aut judicare, yaitu
asas hukum yang menegaskan bahwa “jika negara melakukan penuntutan, ada
kewajiban negara untuk mengekstradisi”.
Dalam catatan
sejarah, ekstradisi telah dipraktikan sejak tahun 1280 SM antara Raja Ramses II
dari Mesir dan Raja Hattusili III dari Hitites, kemudian diikuti oleh kerajaan
Yunani dan kekaisaran Romawi. Model perkembangan ekstradisi abad tersebut
dilandaskan untuk menjaga stabilitas politik kerajaan sehingga ekstradisi
terbatas pada kejahatan politik. Dalam perkembangannya, ekstradisi pasca abad
ke-20 bukan lagi semata-mata merupakan hak dan kewajiban sebagaimana dinyatakan
dalam suatu perjanjian, melainkan juga bagian dari hak asasi tersangka,
terdakwa, atau terpidana untuk menyatakan pendapatnya terhadap permintaan suatu
negara untuk mengekstradisikan ybs. Hal tersebut pernah dipraktikan oleh Hendra
Raharja yang menolak ekstradisi dirinya dari Austarlia dengan alasan Pemerintah
Indonesia diskrimatif dan tahanan di Indonesia tidak menjamin keselamatan
tersangka.
Dalam teori dan
praktik hukum internasional, ekstradisi memiliki empat karakter, yaitu ekstradisi
sebagai suatu kewajiban negara, ekstradisi tanpa perjanjian, ekstradisi dengan
perjanjian bilateral, dan ekstradisi dengan perjanjian multilateral. Kembali
pada perdebatan absennya perjanjian ekstradisi antara Indonesia dengan
Singapura yang menjadikan Singapura sebagai safe
heaven bagi kejahatan kerah putih, Romli Atmasasmita membeberkan bahwa
ekstradisi dapat dilakukan tanpa adanya perjanjian. Menurut Romli, UU 1/1979
tentang Ekstradisi membolehkan ekstradisi dilaksanakan dengan perjanjian
ekstradisi atau tanpa perjanjian ekstradisi, tetapi cukup berdasarkan prinsip
resiprositas. Atas dasar ketentuan UU tersebut, Indonesia mengakui perjanjian
internasional merupakan sumber hukum, dan juga “comity” atau “arrangement”
diakui sebagai sumber hukum tidak tertulis, sepanjang kedua negara
dipenuhi/dijamin ditaatinya prinsip resiprositas. Namun demikian, perlu juga
dicatat bahwa ekstradisi tanpa perjanjian sepenuhnya dilandaskan pada pemikiran
aliran monistik mengenai hubungan antara hukum nasional dan hukum internasional
yang banyak dianut di negara-negara penganut sistem hukum civil law dibandingkan dengan negara penganut hukum common law.
Sementara
ekstradisi dengan perjanjian bilateral menempati posisi yang kuat di antara
negara anggota PBB, ekstradisi dengan perjanjian multilateral lazim dipraktikan
di organisasi regional, seperti Uni Eropa, Liga Arab, dan negara yang tergabung
dalam Commonwealth Nations. Romli
berpendapat bahwa terdapat kecenderungan di masa mendatang untuk memunculkan
suatu “common law of extradition” dan suatu saat diharapkan dapat menghasilkan
suatu “Universal Convention on Extradition” yang dapat dijadikan landasan hukum
ekstradisi yang berlaku bagi seluruh negara anggota PBB.
Uraian khusus
pada Bab II yang menarik untuk dicermati adalah perubahan pandangan masyarakat
internasional terhadap pengecualian atas prinsip nasionalitas dan prinsip ne bis in idem (not twice in the same thing),
terutama setelah perkembangan pemajuan hak-hak ekonomi, sosial, hak sipil dan
hak politik diadopsi dan diberlakukan sebagai bagian dari hukum internasional. Perkembangan
ekstradisi sejak awal kelahirannya pada abad 15—16, disepakati bahwa yang dapat
diekstradisikan hanya kejahatan politik (makar) dan kejahatan penodaan terhadap
agama. Perkembangan ekstradisi selama tahun 1700 dan awal 1800an, justru
kejahatan politik termasuk kejahatan tidak dapat diekstradisi (non-extraditable
crime) sampai dengan tahun 1830-an. Gagasan bahwa tersangka tidak dapat
diekstradisikan untuk tindak pidana yang memiliki motivasi politik, dikemukakan
oleh Belgia dan Perancis. Pengakuan tersebut dikuatkan di dalam MLE UN 1990
yang menegaskan bahwa, kejahatan politik merupakan kejahatan yang tidak dapat diekstradisi-kan
dan bersifat wajib (mandatory obligation).
Lebih jauh lagi,
pada bab ini Romli menjelaskan tentang prinsip-prinsip penolakan ekstradisi,
seperti
- Prinsip Prinsip Kekecualian untuk Tindak Pidana Politik,
- Prinsip Penolakan ekstradisi atas dasar keyakinan bahwa penuntutan akan dilakukan atas dasar perbedaan ras,agama, etnis, pendapat politik, jenis kelamin, dan kebangsaan.
- Prinsip penolakan atas dasar kejahatan yang dimintakan ekstradisi adalah kejahatan militer
- Prinsip Double Jeopardy atau Non-bis in iden sebagai alasan penolakan ekstradisi
- Prinsip tidak meng-ekstradisi jika terhadap seseorang yang dimintakan ekstradisi telah dijatuhi hukuman in absensia di negara peminta
- Prinsip penolakan ekstradisi didasarkan atas imunitas dari penuntutan atau karena daluarsa (lapse of time)
- Prinsip Spesialitas (The Rule of Specialty)
- Prinsip Double Criminality (Dual Criminality)
- Prinsip Tidak Menyerahkan Warga Negara (Non- Extradition of Nationals)
- Prinsip penolakan Ekstradisi atas dasar peradilan yang tidak jujur dan perlakuan yang merendahkan martabat kemanusiaan.
 |
| PM Thailand (2001--2006), Thaksin Sinawatra |
 |
| Presiden Peru (1990--2000), Alberto Fujimori |
Untuk memperoleh
perkembangan terkini mengenai ekstradisi, pada bab III diuraikan praktik
ekstradisi negara Uni Eropa yang dideklarasikan pada tahun 2002 dan berlaku
efektif pada tahun 2004. Model ekstradisi di Uni Eropa yang dikenal dengan
istilah “surrender” merupakan contoh
aktual dan relevan bagi ASEAN baik dilihat dari sisi geografis, cultural,
maupun dari sisi sistem hukum yang berlaku.
Perkembangan
terkini, alasan kejahatan politik dihapuskan di banyak negara dan syarat-syarat
prinsip penolakan ekstradisi telah banyak dikurangi. Kecenderungan pelaksanaan
ekstradisi saat ini adalah memberikan hak yang lebih banyak kepada seseorang yang
diminta untuk diekstradisi dan juga dijadikan bahan pertimbangan bagaimana
orang ybs diperlakukan atau dihukum di negara Peminta. Persyaratan dimaksud
antara lain tidak boleh dilaksanakan atas dasar gender, ras, kebangsaan, asal
etnis atau paham politik. Kecenderungan lain dari perkembangan pelaksanaan ekstradisi
adalah mengurangi prosedur yang tidak perlu termasuk komunikasi langsung dan
prosedur (ekstradisi) yang disederhanakan.
Prinsip
penolakan ekstradisi atas dasar nasionalitas merupakan prinsip yang mutlak dan
menyulitkan efektivitas ekstradisi. Jika prinsip ini dipertahankan setidak-tidaknya
dapat dituntut dan diadili di negara asal warga negara ybs. Perkembangan
terkini, banyak negara yang diminta membolehkan ekstradisi dilakukan terhadap
warga negara sendiri dengan syarat jika setelah dituntut dan diputus oleh
pengadilan di Negara yang Meminta, dapat
dikembalikan ke negara asalnya untuk melaksanakan hukuman, sebagaimana telah
dilaksanakan antara Belanda dan Perancis. Prinsip penolakan ektradisi atas
dasar nasionalitas juga tidak dianut lagi antara Thailand dan Amerika Serikat,
dan antara Negara-negara yang tergabung dalam “Commonwealth Nations”.
Bab IV berisi
pandangan dan sikap penulis terhadap perkembangan ekstradisi. Perjanjian-perjanjian
dan perundang-undangan tentang ekstradisi serta terlibatnya dua negara atau
lebih dalam suatu kasus ekstradisi, menunjukkan bahwa ekstradisi dapat
dipandang sebagai bagian hukum internasional dan juga sebagai bagian hukum
nasional. Oleh karena itu ekstradisi sebagai suatu pranata hukum secara resmi
telah diakui dan diatur dalam hukum internasional dan hukum nasional. Akan
tetapi, perkembangan ekstradisi sebagai “spesies dari genus hukum pidana
internasional” yang sangat telah lambat memunculkan bentuk kerja sama
internasional lainnya, seperti bantuan hukum timbal balik dalam masalah
pindana, transfer terpidana, transfer proses beracara, dan investigasi bersama.
Meskipun demikian, pelbagai bentuk kerja sama internasional dalam bidang hukum
tersebut tetap tidak cukup mampu mengimbangi dan menyertai kecepatan modus
operandi kejahatan internasional.
Meskipun
perjanjian ekstradisi bagi Indonesia bukan masalah hukum baru, buku mengenai
hukum ekstradisi merupakan substansi yang relatif baru dalam kepustakaan hukum
Indonesia. Romli Atmasasmita mengemukakan bahwa niat menulis buku ini semakin
menguat ketika mengamati pemahaman keliru beberapa pejabat tinggi pemerintah
yang belum dapat memahami tentang pengertian, lingkup, serta objek ekstradisi
dalam hukum internasional; dan ekstradisi sebagai sarjana hukum untuk
meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemberantasan (penindakan) kejahatan
yang bersifat lintas batas territorial dan kejahatan transnasional. Masih ada
yang keliru menyamakan ekstradisi dan bantuan hukum timbal balik dalam masalah
pidana (mutual legal assistance in
criminal matters) baik di kalangan pejabat tinggi pemerintah maupun para
sarjana hukum. Dengan terbitnya buku ini, maka diharapkan dapat menguatkan
pemahaman para sarjana hukum, terutama yang menggeluti hukum internasional,
dalam bidang ekstradisi.

.jpg)